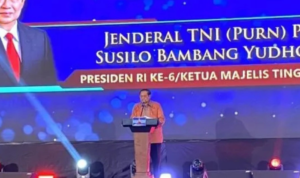Mudabicara.com_Kita tahu bahwa sejak lebih dari satu dekade terakhir, praktik pemilihan kepala daerah yang dicanangkan untuk diwakilkan oleh dewan rakyat terus-menerus digaungkan dalam ruang publik. Dalam buku Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia yang dituliskan Hadiz (2010) menyebutkan wacana ini tidak pernah hadir dalam ruang hampa, melainkan selalu dibarengi dengan kepentingan politik koalisi pemerintahan yang ingin mempertahankan kekuasaan agar berlangsung lebih lama.
Upaya tersebut hampir mustahil dipisahkan dari urusan lumbung-lumbung ekonomi daerah, di mana kekuasaan politik berkelindan erat dengan akses terhadap sumber daya, proyek, dan anggaran publik. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa demokrasi lokal di Indonesia kerap menjadi arena konsolidasi kekuatan oligarki, bukan ruang kompetisi yang sehat bagi kepentingan.
Baca Juga: KPK Ungkap Modus Korupsi Berlapis, OTT Tak Lagi Andalkan Transaksi Langsung
Mietnerz (2013) dalam kajiannya Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia menyatakan praktik ini semakin diperparah oleh ketidakmampuan atau ketidakberanian masyarakat sipil untuk secara terbuka menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh koalisi pemerintah tersebut adalah keliru. Lemahnya kontrol publik, minimnya gerakan kritis yang berkelanjutan, serta normalisasi praktik politik transaksional membuat wacana pemilihan tertutup seolah dianggap wajar. Padahal, dalam demokrasi yang sehat, masyarakat sipil seharusnya menjadi kekuatan penyeimbang terhadap hasrat kekuasaan elite, bukan justru menjadi penonton pasif.
Tulisan opini ini saya beri judul Dimulai dari Kotak Suara, karena saya meyakini bahwa seluruh krisis demokrasi lokal kita bermula dari titik tersebut. Kotak suara seharusnya menjadi simbol paling nyata dari kedaulatan rakyat. Namun dalam penelitian Aspinall & Sukmajati (2015) “Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014” menyatakan, dalam praktiknya, demokrasi yang dijadikan landasan ideal ternyata tidak selalu melahirkan pemimpin yang mumpuni dan berintegritas.Realitas politik menunjukkan bahwa suara rakyat dapat dibeli. Jika berkaca pada temuan dan fakta di lapangan, praktik serangan fajar bukan lagi penyimpangan insidental, melainkan bagian dari pola sistemik dalam kontestasi politik lokal.
Kontradiksi inilah yang menandai krisis demokrasi kita hari ini. Di satu sisi, demokrasi diagungkan sebagai sistem yang memberi ruang partisipasi luas bagi rakyat. Di sisi lain, praktik di lapangan justru menunjukkan degradasi nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Politik uang mereduksi pilihan politik menjadi transaksi sesaat, sementara pemimpin yang lahir dari proses semacam ini cenderung lebih loyal pada modal dan jaringan kekuasaan dibandingkan pada kepentingan publik. Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan menunjukkan adanya korelasi kuat antara tingginya biaya politik dan kecenderungan korupsi kepala daerah terpilih.
Baca Juga: Perombakan Besar di Bea Cukai, Purbaya: “Sebagian Dirumahkan, Sebagian Tidak”
Menurut keyakinan Kami, jika kondisi ini terus dibiarkan, praktik tersebut akan berlangsung lama dan semakin mengakar. Yang paling dirugikan bukanlah elite politik yang silih berganti memegang kekuasaan, melainkan rakyat itu sendiri. Dalam konteks inilah, krisis demokrasi tidak dapat diselesaikan dengan menarik kembali hak rakyat melalui pemilihan tertutup. Pemilihan tertutup bukan solusi atas rusaknya demokrasi elektoral, melainkan bentuk lain dari pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat yang justru memperdalam jarak antara penguasa dan warga negara.