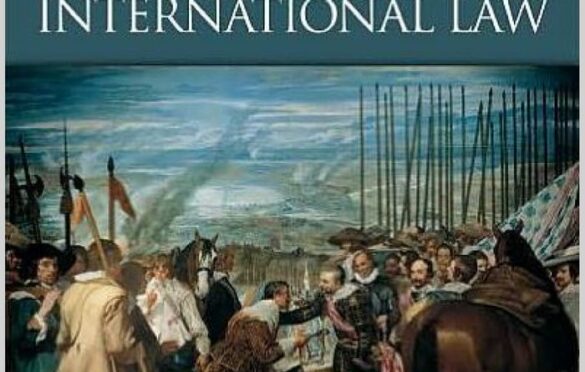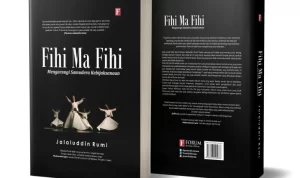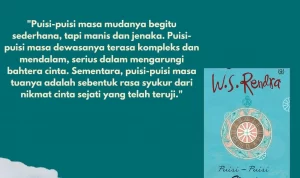Mudabicara.com_Kali ini kita akan membahas buku Jack L. Goldsmith dan Eric A. Posner. Jack Landman Goldsmith merupakan salah satu profesor di Harvard Law School sedangkan Eric Andrew Posner merupakan profesor hukum di Universitas Chicago. Kedua profesor ini mempunyai pengaruh dan menancapkan fondasi pengetahuan tentang kajian hukum terutama Internasional Law.
The Limit Of Internasional Law
Buku The Limit of Internasional Law mencoba menjelaskan tentang bagaimana Internasional Law berkerja, dimana batasannya, serta dilema-dilema apa yang dihadapinya. Selama kemunculannya, hukum internasional dipandang sebagai hukum yang syarat akan kepentingan. Hukum internasional tidak mempunyai kekuatan yang efektif dalam penegakan aturan serta hukum internasional dipandang hanya akan menjadi aturan main bagi negara-negara maju dalam mendistribusikan kekuasaan serta kepentingan kepada negara-negara lemah.
BACA JUGA : BUKU POPULISME ISLAM DI INDONESIA DAN TIMUR TENGAH
Jack L. Goldsmith dan Eric A. Posner menawarkan pendekatan yang menarik dalam melihat hukum internasional. Dua tokoh ini berpendapat bahwa suatu negara akan mematuhi hukum internasional bila mana kepentingan nasional negara tersebut terwakili. Artinya hukum internasional hanya sebagai bentuk aturan main dalam melihat bagaimana kerjasama antar negara terbentuk. Bentuk kerjasama tentu berupa aturan yang mengikat satu sama lain. Disaat kerjasama tidak menguntungkan salah satu pihak tentu secara rasional negara dapat tidak mengikuti aturan dalam kerjasama tersebut. Tentu menjadi alasan yang rasional bahwa mengapa harus mengikuti hukum internasional jika merugikan kepentingan nasional.
Pandangan bahwa hukum internasional hanya sebagai kepanjangan tangan dari kepentingan politik dan ekonomi membuat hukum internasional memainkan peran penting dalam retorika hubungan internasional. Pijakan awal hukum internasional tentu tidak bisa lepas dari realitas politik yang terjadi pada masyarakat internasional. Bahwa proses globalisasi yang ditandai dengan industrialisasi, perdagangan, dan pasar bebas memaksa negara harus mempunyai kerjasama dan koordinasi yang saling mengikat. Tentu salah satunya menghasilkan hukum internasional.
Namun asumsi diatas membuat definisi hukum internasional menjadi abu-abu. Apakah benar hukum internasional dibuat untuk kepentingan bersama atau malah menjadi alat distribusi kekuasaan bagi negara yang mempunyai kepentingan. Hal itu mengisyaratkan bahwa hukum internsional hanya muncul ketika ada kepentingan bersama tanpa adanya norma yang mengikat secara universal. Sehingga perlu kiranya kajian yang lebih komprehensif antara hukum internasional dan hubungan internasional. Selama ini hubungan internasional dan hukum internasional menjadi kajian yang terpisahkan. Padahal hukum internasional tentu akan berkaitan dan menghidupkan kajian hubungan internasional menjadi lebih menarik serta menantang.
Josep S Nye dalam bukunya Soft Power: The Means To Success In World Politics menjelaskan bahwa peran diplomasi hari ini mengalami pergeseran. Negara tidak lagi menjadi aktor utama diplomasi namun peran diplomasi kini juga bisa dilakukan oleh Non-Governmental Organization (NGO), Multinational Corporation (MNC), ataupun individu. Pergeseran ini tentu akan berpengaruh juga terhadap hukum internasional tertutama dalam konteks ekonomi global dan pasar bebas. Sebagai entitas, negara tentu akan menancapkan kepentingan dan pengaruhnya hingga kepentingan negaranya terpenuhi.
Memang sulit melihat aspek kepentingan negara terutama dalam hukum internasional. Bagaimana tidak, awalnya hukum internasional hanya dipandang sebagai aturan kerjasama dan koordinasi antar dua negara atau sekelompok kecil negara yang telah disepakati bersama. Kata disepakati tidak mengidentifikasikan bahwa negara tersebut mengikuti aturan. Tetapi hal tersebut hanya sebatas ketika kepentingan pribadi ataupun kepentingan negara mampu terakomodasi atas hukum internasional maka akan patuh dan mengikutinya. Ada juga hukum internasional digunakan sebagai alat untuk meraup keuntungan negara sendiri dan merugikan negara lain. Artinya hukum internasional dalam bentuk kerjasama dan koordinasi masih mempunyai kekurangan yakni efektifitas dalam penegakannya. Sebab hukum internasional masih tergantung pada kepentingan dan permintaan.
Dalam bagian dua The Limit of Internasional Law menjelaskan tentang perjanjian kerjasama. Mulai dari teori kesepakatan antar negara, hak asasi manusia, dan perdagangan internasional. Teori kesepakatan antar negara artinya ketika negara tersebut melakukan perjanjian dan menyepakatinya. Maka secara langsung kesepakatan tersebut menjadi produk hukum internasional yang mengikat kedua belah pihak. Selain membahas perjanjian kerjasama tentu hukum internasional menaruh perhatian khusus soal kemanusian yakni hak asasi manusia internasional. Salah satu yang dibahas didalamnya adalah diskriminasi terhadap perempuan, dikriminasi rasial, dan genosida. Dan terakhir membahas tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional menjadi isu paling menarik untuk dibahas bila berbicara tentang kepentingan dan kekuasaan apalagi dikaitkan dengan hukum internasional. Sebab sampai saat ini hukum internasional tidak mampu berbicara banyak soal ketimpangan dalam perdagangan internasional.
World Trade Organization (WTO)
Mari kita lihat Efek dari globalisasi yakni memaksa adanya industrialisasi dan pasar bebas. Fenomena ini akhirnya membuat banyak negara melakukan kerjasama dengan dalih kesejahteraan. Padahal faktanya tidak semua berjalan demikian. Banyak hasil perjanjian yang menjadi hukum internasional kemudian hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Kita ambil saja beberapa isu kasus yang dapat menjadi acuan bahwa pernyataan di atas benar. Salah satunya bisa kita lihat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh World Trade Organization (WTO)
Pertama, isu tentang kelaparan global. Isu ini membuat berbagai kebijakan WTO yang lebih menekankan produksi pangan untuk ekspor ketimbang untuk konsumsi lokal. Petani-petani di negara berkembang yang sebelumnya mampu mencukupi kebutuhan pangannya sendiri serta komunitas-komunitasnya dipaksa untuk meninggalkan tanah dan ladang mereka. Tanah dan ladang mereka lantas diganti oleh agribisnis berskala besar yang menghasilkan barang-barang mewah berkeuntungan tinggi. Barang-barang tersebut tak lain ditujukan untuk kepentingan ekspor kenegara-negara kaya. Kini dalam keadaan tak bertanah, masyarakat di negara berkembang mulai dililit kesulitan dan kelaparan.
Fakta menunjukan bahwa sejumlah petani yang dulu mampu berswasembada terpaksa pindah ketempat lain bahkan mereka merantau ke negara lain dan terpaksa berkompetisi untuk memperebutkan peluang kerja yang amat terbatas. Penyebab dari semua itu adalah komoditas pangan tidak diproduksi dan disalurkan secara layak dan adil. Selain itu masyarakat miskin di negara berkembang yang tanahnya subur hanya mampu berdiri dengan tangan kosong serta perut kosong memandang hasil panen yang berlimpah diekspor demi uang semata.
Fenomena ini tentu dalam waktu singkat akan menguntungkan salah satu pihak sementara dalam jangka waktu yang lama akan merugikan banyak orang. Sebab bebicara soal kelaparan itu semua hanya persoalan distribusi yang timpang serta masalah ketidakadilan bukan masalah kekurangan pangan. Dalam konteks peralihan tanah pertanian menjadi industri terutama di Asia Tenggara dapat dibaca pada buku Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia karya Derek Hall, Philip Hirsch, & Tania Murray Li. Buku tersebut menjelaskan lebih jelas tentang problematika pertanahan di Asia Tenggara pasca adanya gelombang industrialisasi dan ekspansi pasar bebas.
Kedua isu tentang investasi, banyak kelompok masyarakat sipil maupun pemerintahan di negara-negara berkembang semakin merasa getir dan kecewa betapa kepentingan negara dan rakyatnya telah dimarjinalisasi dan bahkan diinjak-injak oleh WTO. Salah satu isu santer yang dibicakan yakni mengenai isu investasi. Negara-negara kaya mendesak masuknya peraturan baru yang memberi hak kepada investor asing. Hal ini tentu berakibat pada mudahnya para investor melakukan investasi diberbagai negara dan dapat beropeasi secara bebas.
Selain itu berbagai tekanan kepada negara-negara anggota WTO juga akan ditingkatkan guna meliberalisasi aliran investasi dan memberikan national treatment kepada para investor dan perusahaan asing. Artinya investor asing harus diperlakukan sejajar atau bahkan lebih baik daripada investor lokal. Jika hal ini benar terjadi bisa dipastikan bahwa pemerintah akan kehilangan sebagian besar hak yang mereka miliki dalam mengatur sejumlah tindakan para investor asing. Lebih lanjut masuknya asas-asas kebijakan investasi ke WTO akan semakin memperbesar wewenang dan kekuasaan WTO, Akibatnya secara praktis negara-negara berkembang akan menghadapi ancaman yang sangat serius.
Maka tidak mengherankan jika liberalisasi investasi pada akhirnya akan mengakibatkan negara-negara maju akan memperoleh apa yang mereka inginkan sedangkan negara-negara berkembang tidak akan mampu mempertahankan kelangsungan hidup ataupun lebih memprioritaskan para investor perusahaan lokal ataupun pertanian rakyat. Sebab secara perbandingan tentu tidak apple to apple jika perusahaan lokal bersaing dengan perusahaan asing.
Dengan demikian, sulit bagi negara-negara berkembang untuk melawan dan menahan serangan gencar investasi. Bagaimanapun juga negara-negara berkembang akan menghadapi ancaman ketika produk-produk lokal mereka terjual dengan harga yang sangat rendah lantaran bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang lebih besar. Bahkan besar kemungkinan perusahaan lokal tersebut akan diakuisisi oleh perusahaan transnasional atau asing tersebut sebab mengalami gagal produksi dan bangkrut.
Ketiga isu tentang kebijakan persaingan. Isu tersebut sebenarnya sudah dibahas oleh Uni Eropa (UE), UE menyatakan bahwa apa yang dianggap sebagai asas-asas dari perlakuan nasional dan non-diskriminasi seharusnya diterapkan melalui proses kesepakan baru. Hal ini dimaksudkan agar pemberlakuan undang-undang domestik berikut praktek-praktenya dapat mendukung perusahaan lokal untuk mendapat keuntungan. Sebab selama ini undang-undang domestik bertentangan dengan falsafah persaingan bebas.
Sebagai contoh jika muncul kebijakan yang memberi hak impor dan distribusi atau kebijakan apapun yang lebih menguntungkan peusahaan lokal. Katakanlah memberikan jalur pemasaran yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan internasional maka besar kemungkinan hal tersebut akan dipermasalahkan oleh WTO. Bisa jadi malah penertiban dan sanksi akan diterapkan.
Tunduknya Hukum Internasional Pada WTO
Fakta ini menunjukan bahwa negara maju selalu menekankan berbagai kebijakan yang selalu merugikan negara berkembang. Atas nama perdagangan dan investasi banyak perusahaan asing melakukan diskriminasi produk dan mereka diperbolehkan melakukan pemasaran dan bersaing dengan perusahaan lokal. Perusahaan internasional mempunyai kedudukan yang sama dalam proses perdagangan bebas sehingga siapa yang mempunyai modal yang besar merakalah yang akan menguasai pasar.
Sementara itu, negara-negara berkembang sendiri menyatakan bahwa jika perusahaan-perusahaan yang lebih kecil diperlakukan setara dengan para perusahaan asing raksasa, maka kebanyakan dari mereka tidak akan mampu bertahan hidup. Barangkali beberapa di antaranya masih bisa hidup sebab mereka memiliki struktur dan suprastruktur yang baik dalam sistem distribusi. Sistem distribusi tersebut biasanya dibangun berdasarkan pada pengetahuan mereka yang mendalam tentang kondisi tingkat lokal yang mampu memberikan sedikit keuntungan bagi mereka untuk bisa bersaing dengan sejumlah perusahaan asing yang lebih banyak difasilitasi. Akan tetapi operasi jalur-jalur distribusi lokal semacam itu biasanya juga sangat rentan terhadap serangan dari kebijakan persaingan dalam WTO. Pasalnya negara-negara maju berkencenderungan besar akan memaksa perusahaan-perusahaan lokal untuk membuka juga jalur-jalur pemasaranya bagi para pesaing asing.
Saat ini banyak negara berkembang mengemukakan bahwa dengan memberikan perlakuan yang menguntungkan bagi sejumlah perusahaan lokal pada hakekatnya merupakan tindakan pro-kompetitif. Itu berarti bahwa berbagai perusahan lokal yang lebih kecil tersebut dibekali sejumlah kelebihan agar mampu menghadapi kekuatan perusahaan asing. Kalau tidak begitu mereka akan memonopoli pasar lokal. Memberi hak yang sama kepada perusahaan-perusahaan internasional praktis akan semakin membuat perusahaan-perusahaan lokal baik yang berukuran kecil maupun sedang menjadi kewalahan dan pada akhirnya tersisih dalam lingkup global.
Namun pernyataan-pernytaan semacam itu tentu saja tidak akan diterima oleh negara-negara maju. Mereka pasti akan mendesak agar perusahaan-perusahaan raksasa milik mereka diberi lapangan bermain yang rata untuk bersaing dalam kedudukan yang setara dengan perusahaan-perusahaan lokal yang lebih kecil. Mereka menginginkan agar interpretasi mereka tentang kompetisi dan persaingan yang ironisnya besar kemungkinan mengarah pada terjadinya monopoli perusahaan asing atas pasar-pasar negara berkembang dimasukan dalam peraturan WTO melalui putaran baru dalam perundingan perdagangan dunia.
Tiga isu yang penulis ungkapkan di atas tentang kelaparan global,isu investasi dan persaingan bebas tentu sangat merugikan bagi negara-negara yang tingkat ekonomi dan pembangunan rendah. Oleh sebab itu maka bagi negara berkembang, perusahaan lokal, pertanian rakyat serta liberalisasi perdagangan semacam itu membuat mereka menjadi kaum pinggiran. Artinya liberalisasi memang diperlukan dalam konteks pembangunan hanya saja hal tersebut harus dilakukan secara selektif dan selaras dengan mempertimbangkan kemampuan negara itu sendiri.
Tindakan yang dilakukan dengan cara memaksa negara-negara berkembang melakukan perdagangan dan investasi merupakan distorsi yang sesungguhnya atas sistem perdagangan multilateral dan internasional law. Semakin cepat pemimpin politik dan perusahaan-perusahaan negara maju menyadari hal ini akan semakin baik. Kalau tidak WTO akan berjalan kearah yang salah. Bahkan masa depan yang suram pun akan selalu membayangi seluruh negara, masyarakat, dan tentu rakyat akan menjadi tumbal dari hancurnya kehidupan ekonomi dan sosial serta luluh-lantaknya lingkungan hidup. Disinilah mengapa ada The limit of Internasional Law.
Terbaru kita bisa lihat juga dari beberapa kebijakan luar negeri Donal Trump yang membatalkan kerjasama ekonomi salah satunya Trans Pacific Partnership (TPP). Trump memandang bahwa kesepakatan tersebut berdampak buruk bagi perdagangan, pekerja Amerika Serikat (AS) dan memungkinkan negara lain mengambil keuntungan. Pada akhirnya pada tanggal 27 Januari 2017 Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menarik AS dari TPP dan hal tersebut dilakukan demi masa depan pekerja Amerika Serikat. Sebab Trump memang mangunakan falsafah proteksionisme ekonomi terhadap Amerika.
Akhirnya setelah menjelaskan tentang panjang lebar tentang perdagangan internasional maka sampailah pada beberapa kesimpulan bahwa internasional law tidak mempunyai peran yang signifikan ketika masuk dalam ruang-ruang ekonomi dan perdagangan. Ada ruang yang dilematis ketika aturan main perdagangan, permodalan dan persaingan hanya dikuasai oleh negara-negara maju. Negara dunia ketiga seperti Indonesia semacam menjadi penonton sekaligus pengikut yang mau tidak mau harus mengikuti aturan main meskipun itu merugikan. Hasil-hasil Memorandum of Understanding (MoU) sebuah kerjasama multilateral juga merupakan produk hukum internasional yang tentu mengikat meski faktanya bila berbicara ekonomi akan selalu debatable dan dilematis.
Akhinya untuk memahami apa yang dimaksud the limit of Internasinal Law dalam buku Jack L. Goldsmith dan Eric A. Posner memang harus memahami seluk beluk kepentingan negara baik secara politik dan ekonomi.
Penulis : Mahfut Khanafi (CEO Mudabicara)